Pendidikan Indonesia di Masa Kerajaan - Sangat penting kiranya bagi kita untuk mengetahui bagaimana pendidikan di Indonesia pada masa-masa kerajaan yang pernah ada di Negeri tercinta. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit share tentang bagaimana pendidikan Indonesia di masa-masa kerajaan. Bahwa pendidikan di masa kerajaan dimulai dari kerajaan Sriwijaya. Pada kerajaan Mataram kuno terkenal atau berpusat di Jawa Tengah dan aktivitas pendidikannya yaitu; menterjemahkan buku-buku agama Budha, menterjemahkan buku-buku lain ke bahasa Jawa kuno seperti Ramayana dan perguruan tinggi di masa kerajaan Mataram kuno sudah meliputi Fakultas Agama, Fakultas Sastra, Fakultas Bangunan atau Teknik Bangunan. Selain kerajaan Mataram, juga ada kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam.
- Kerajaan Hindu-Buddha
Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita Ramayana.
- Kerajaan Islam
Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad 7.
 Menurut sumber-sumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini nampak pada Tahun 100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Bani Umayyah meminta dikirimkan da'i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi: “Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu- bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Allah. Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.” Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama 'Sribuza Islam'. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Budha.
Menurut sumber-sumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini nampak pada Tahun 100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Bani Umayyah meminta dikirimkan da'i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi: “Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu- bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Allah. Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.” Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama 'Sribuza Islam'. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Budha.Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225 H atau 12 November 839 M. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim bernama Bayanullah.
Kesultanan Islam kemudian semikin menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut.
Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubaligh merupakan utusan dari pemerintahan Islam yang datang dari luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubaligh ini bekerja melalui cara berdagang, para mubaligh inipun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli kerajaan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kerajaan Islam penting termasuk di antaranya: Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku.
Demikian, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dalam menggali sejarah pendidikan di Indonesia.





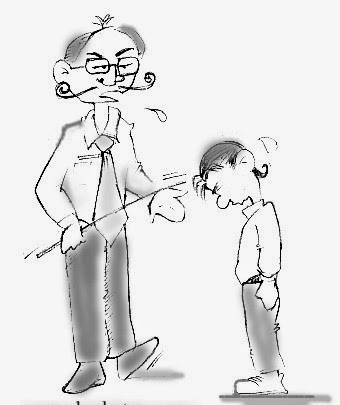
.jpg)








