Prinsip-prinsip Pendekatan dalam Pembelajaran Anak Usia Dini - Pada kesempatan kali ini, membumikan pendidikan akan share mengenai prinsif-prinsif pendekatan dalam pembelajaran anak usia dini. Bahwa dalam dokumen Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, dinyatakan bahwa “Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik”.
Pendidikan anak usia dini pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip PAUD sebagai berikut:
Pendidikan anak usia dini pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip PAUD sebagai berikut:
Berorientasi pada Kebutuhan Anak
Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Menurut Maslow kebutuhan anak yang sangat mendasar adalah kebutuhan fisik (rasa lapar dan haus), anak dapat belajar apabila tidak dalam kondisi lapar dan haus. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan keamanan (merasa aman, terlindung dan bebas dari bahaya), dan kebutuhan rasa dimiliki dan disayang (berhubungan dengan orang lain, rasa diterima dan dimiliki).
 |
| Kebutuhan Anak |
Sesuai dengan Perkembangan Anak
Pembelajaran untuk anak usia dini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik usia maupun dengan kebutuhan individual anak. Perkembangan anak mempunyai pola tertentu sesuai dengan garis waktu perkembangan. Setiap anak berbeda perkembangannya ada yang cepat ada yang lambat. Oleh karena itu, pembelajaran anak usia dini harus disesuaikan baik lingkup maupun tingkat kesulitannya dengan kelompok usia anak.
Mengembangkan kecerdasan anak
Pembelajaran anak usia dini hendaknya tidak menjejali anak dengan hafalan, tetapi mengembangkan kecerdasaanya. Penelitian di bidang neuroscience (ilmu tentang saraf) menemukan bahwakecerdasan sangat dipengaruhi oleh banyaknya sel saraf otak, hubungan antar sel saraf otak, dan keseimbangan kinerja otak kanan dan otak kiri. Pada saat lahir sel otak sudah terbentuk semua yang jumlahnya mencapai 100-200 miliar, dimana setiap sel dapat membuat hubungan dengan 20.000 sel saraf otak lainnya, atau dengan kata lain dapat membentuk kombinasi 100 miliar x 20.000. Oleh karena itu, anak usia (0-8 Tahun) merupakan usia yang sangat kritis bagi pengembangan kecerdasan anak. Sayangnya, banyak guru, orang tua, dan pendidik anak usia dini yang “mengunci mati” sel otak tersebut untuk menjalankan fungsi kapasitasnya yang tak terhingga (unlimited capacity to learn) (Semiawan, 2004).
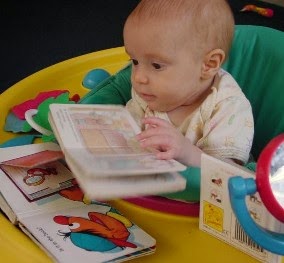 |
| Stimulasi Kecerdasan Anak Sejak Dini |
Belajar melalui bermain
Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini, dengan menggunakan strategi, metode, materi/bahan, dan media yang menarik agar mudah diikuti oleh anak. Melalui bermain anak diajak untuk berekplorasi (penjajagan), menemukan, dan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya.
Belajar dari kongkrit ke abstrak, sederhana ke kompleks, gerakan ke verbal, dan dari sendiri ke sosial
Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang kongkrit ke abstrak, dari konsep yang sederhana ke kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial. Agar konsep dapat dikuasai dengan baik hendaknya guru menyajikan kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang.
Anak sebagai Pembelajar Aktif
Anak melakukan sendiri kegiatan pembelajarannya, sehingga anak aktif, guru hanya sebagai fasilitator atau mengawasi dari jauh.
Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya di lingkungannya
Ketika anak berinteraksi dengan teman sebayanya, maka anak akan belajar, begitu juga ketika anak berinteraksi dengan orang dewasa (guru, orangtua)
Menggunakan lingkungan yang kondusif
Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain.
 |
| Lingkungan yang Kondusif Menarik Minat Anak |
Merangsang kreativitas dan inovasi
Proses kreatif dan inovatif dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis, dan menemukan hal-hal baru.
Mengembangkan kecakapan hidup
Pendidikan anak usia dini mengembangkan diri anak secara menyeluruh (the whole child). Berbagai kecakapan dilatihkan agar anak kelak menjadi manusia seutuhnya. Bagian dari diri anak yang dikembangkan meliputi bidang fisik-motorik, intelektual, moral, sosial, emosi, kreativitas, dan bahasa. Tujuannya ialah agar kelak anak berkembang menjadi manusia yang utuh yang memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, cerdas dan terampil, mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Mengembangkan kecakapan hidup dapat dilakukan melalui berbagai proses pembiasaan. Hal ini dimaksudkan agar anak belajar untuk menolong diri sendiri (mandiri), disiplin, mampu bersosialisasi, dan memperoleh bekal keterampilan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidupnya.
Memanfaatkan potensi lingkungan
Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik/guru.
Sesuai dengan kondisi sosial budaya
Pembelajaran anak usia dini harus sesuai dengan kondisi sosial budaya. Apa yang dipelajari anak adalah persoalan nyata sesuai dengan kondisi dimana anak berada. Berbagai objek yang ada disekitar anak, kejadian, dan isu-isu yang menarik dapat diangkat sebagai tema persoalan belajar.
Stimulasi secara holistik
Pembelajaran anak usia dini sebaiknya bersifat terpadu atau holistik. Anak tidak belajar mata pelajaran tertentu, seperti IPA, Matematika, Bahasa secara terpisah, tetapi fenomena dan kejadian yang ada disekitarnya. Melalui bermain dengan air anak dapat belajar berhitung (matematika), mengenal sifat-sifat air (IPA), menggambar air mancur (seni), dan fungsi air untuk kehidupan (IPS).
Sekian, semoga bermanfaat...
Sekian, semoga bermanfaat...
















